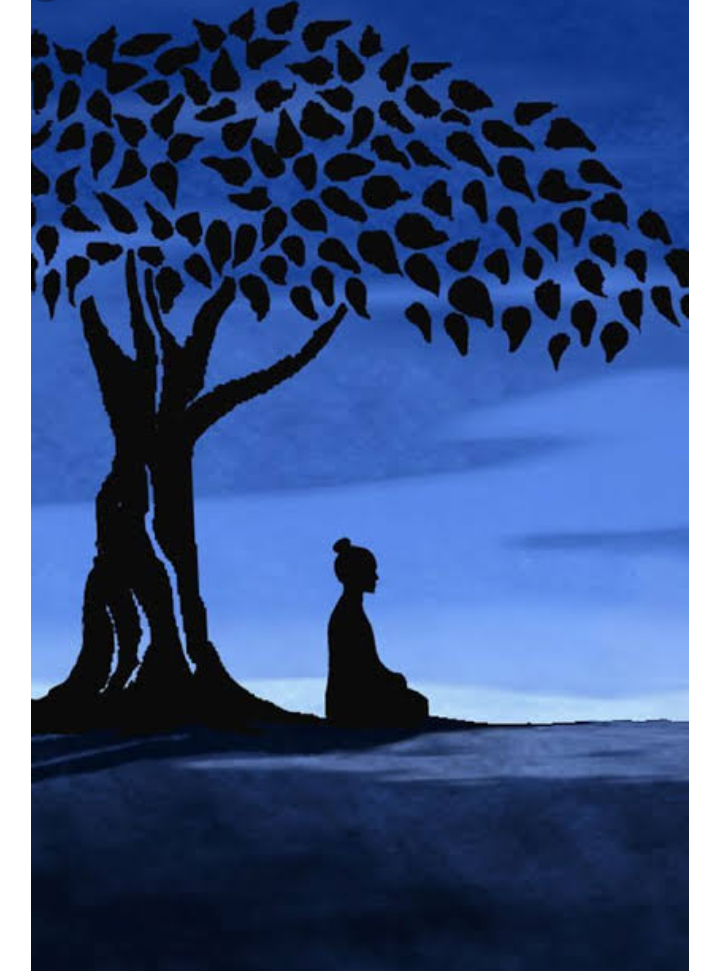Penulis: Ghina Syauqila
TIDAK ADA GUNANYA!!!
Dilempar. Semuanya. Dihempas. Seluruhnya. Hingga tercerai-berai helai demi helai. Butir-butir lelehan peluhnya, sungai-sungai kecil air matanya, gelegak-gelegak asanya, hamparan-hamparan doanya, terbanting-banting. Tak lagi berarti.
Lamia, Sambara, Wistara, Kaluna. Mereka merampas segala-galanya, darinya. Men-jajah dan menginvasi mimpi-mimpinya, semudah itu. Hanya dengan kiriman amplop yang menyambangi semalam atau kegadisan yang dibarter dalam satu malam.
IMPIAN ITU SEKARANG DIBELI. BUKAN DIPERJUANGKAN!
Sekarang makna perjuangan telah terlecehkan, lebih rendah daripada apapun, pantas diinjak-injak. Modal menggapai mimpi bukan tekad, usaha, dan harapan lagi. Melainkan tebal kantong, gemuk rekening. Atau paras memabukkan, lekuk tubuh bahenol. Sedangkan Elea, ia tak punya apapun. Kecuali butir-butir lelehan peluhnya, sungai-sungai kecil air matanya, gelegak-gelegak asanya, hamparan-hamparan doanya.
“Laknat kalian semua.”
Ia lantas menyambar ransel lusuh berkedutnya. Mengayunkan kedua tungkai berganti-gantian, sahut-bersahutan, timpal-menimpali, dengan sangat cekatan, kendati napas mulai terpincang-pincang karena tertindih kinerja debaran jantung yang lunglai. Meninggalkan keempatnya yang saling bertatapan heran dan mengangkat pundak di belakang. Kemudian kembali bercengkerama hangat tentang pencapaian masing-masing. Tak ada yang tak bangga dengan pencapaiannya. Sesekali tawa dan sanjungan bergempita.
Hanya Elea yang tak pernah bangga pada pencapaiannya.
Di kamarnya, ia tak dapat mengendalikan tangis. Menumpahkan dan melimpahkan segenap kebencian. Dirinya kesetanan kebencian. Bahkan sejak ia tiba di rumah petang menjelang senja tadi, ia memuntahkan apa-apa saja yang telah menembus pencernaannya. Segelas es teh menyegarkan dan seporsi roti bakar cokelat menggugah selera yang ternyata beracun, terlarang, najis, nista. Mengutuk dirinya yang tadi sempat memuji kenikmatan es teh dan roti bakar cokelat, yang tadi merasa puas karena dapat membasmi rasa lapar dengan keduanya, yang tadi berterimakasih pada Sambara atas traktirannya.
Bisa-bisanya kau memakan sampah-sampah itu, Elea.
Segelas es teh dan seporsi roti bakar cokelat mengenyangkan perut yang ternyata ditukar dengan beberapa lembar uang hasil pekerjaan kantoran haram.
Mulai hari itu pula, Elea tak pernah merasa berharga. Karena apa? Karena dari pertemuan dengan teman-teman buntangnya, ia belajar nilai diri tak memiliki arti apa-apa dibandingkan nilai kantong atau rekening dan nilai paras atau tubuh. Elea tak merasa berharga, karena ia tak punya semuanya.
Elea dulunya pernah merasa sangat berharga. Di kampusnya dulu, meski parasnya tak seelok Lamia; tubuhnya tak semolek Kaluna; barang-barang yang ia miliki, apabila disandingkan dengan barang-barang milik Sambara lebih mirip barang rongsokan; dan sepetak kontrakannya lebih cocok menjadi gudang di rumah semegah istana punya Wistara, ia jauh lebih dihargai daripada keempatnya. Karena apa? Karena semangatnya, mimpi-mimpi besarnya, kepintarannya, keterampilannya, bakatnya, daya juangnya, dan kekuatan karakternya. Rasa-rasanya, hampir semua mahasiswa fakultasnya mengaguminya, menyukai-nya, ingin sepertinya. Ia inspirator bagi kakak-kakak tingkatnya, motivator untuk teman-teman sebayanya, panutan buat adik-adik tingkatnya. Elea salah satu bintang paling terang di kampus. Siapapun senang menyaksikan gemerlap pendarnya, menjadikan hati-hati terpesona.
Kemarin, Elea mahasiswa berprestasi sekaligus aktivis yang aktif berorganisasi, namun juga mencetak nilai terbaik dalam akademik. Meski di luar sana banyak orang yang jauh lebih hebat darinya, tetap, Elea idola mahasiswa fakultasnya. Walau mungkin prestasi yang pernah ia raih tak seberapa, setidaknya ia berprestasi. Sudah. Sejarah prestasinya yang baginya ‘tak seberapa’ itu saja telah menjadi catatan sejarah bertinta emas yang berarti di mata orang lain. Tapi sekarang, bintang bernama Eleanor Hanasta Lanakila itu awawarna. Redup, padam.
—